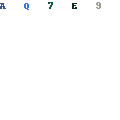Cara menyampaikan pelajaran rumus luas
segitiga dan luas cakram tentu berbeda. Walau sama-sama bertema luas,
ciri dan sifat kedua konsep tersebut berbeda. Rumus luas segitiga
melibatkan penghitungan eksak semata dan terkait dengan persegi panjang,
sedangkan rumus luas cakram pada tingkat SD melibatkan penghitungan
yang harus dinyatakan dalam penaksiran.
Tanpa memahami perbedaan ini,
pemahaman tentang gagasan luas dan keterampilan berhitung eksak serta
penaksiran murid mungkin tak bisa dikuasai. Guru yang tak memahaminya
sangat mungkin akan menyampaikan kedua rumus tersebut bak turun dari
langit dan harus dipercaya. Ketakpahaman guru tentang konsep keilmuan
merupakan cikal-bakal pembelajaran dogmatis. Sebaliknya, pemahaman
keilmuan guru yang mendalam akan menghasilkan kelas dengan suasana
ilmiah dan toleran.
Profesor H. Wu dari Universitas Berkeley menegaskan bahwa content dictates pedagogy in mathematics education
atau bahan ajar mendikte pedagogi dalam pendidikan matematika (Wu,
2004). Dapat dibayangkan, pelajaran geometri dan pengukuran yang
sama-sama membahas luas saja begitu berbeda cara penyampaiannya, apalagi
cara mengajarkan ilmu hayat dan sejarah.
Keanekaragaman metode pembelajaran
merupakan keniscayaan. Tak mungkin ada satu metode pembelajaran yang
sama dan dapat dijejalkan ke semua mata pelajaran di seluruh Indonesia.
Bahkan, sementara pada hari ini seorang guru memilih sebuah metode
pembelajaran tertentu, sangat mungkin pada hari lain guru tersebut
menerapkan metode lain.
Namun, walau berbineka dalam
pembelajaran, pendidikan Indonesia tetap mempunyai unsur kebersatuan,
yakni prinsip. Misalnya, pembelajaran matematika di Merauke dan
pembelajaran seni di Nias berbeda. Alat bantu ajar keduanya berbeda,
tapi harus berprinsip sama, yakni berpusat pada murid. Kedua pendidik
yang mengelola dua mata pelajaran yang berlainan itu perlu berprinsip
sama: tindakan pembelajaran dilakukan terutama demi perkembangan murid.
Keduanya juga perlu berprinsip sama, bahwa perkembangan setiap murid
hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang menempatkan siswa
sebagai pelaku aktif utama dan dengan cara sukacita. Prinsiplah yang
mempersatukan pendidikan Indonesia. Semoga Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dapat segera merumuskan prinsip pendidikan Indonesia.
Adapun anggapan bahwa penyeragaman
kecakapan anak merupakan pemersatu pendidikan Indonesia harus
ditanggalkan. Justru keanekaragaman kecakapan setiap anak yang perlu
dirayakan dan didorong. Jika keanekaragaman berkecambah di negara
kepulauan dengan panjang dari London sampai Turki ini, sungguh tak masuk
akal jika kecakapan warga harus diseragamkan, terutama dengan alat
pemangkas keanekaragaman sistematis seperti ujian nasional. Barang yang
diproduksi pabrik memang perlu distandarkan, tapi pendidikan umum tak
boleh menyeragamkan satu pun anak manusia dan kecakapannya. Pendidikan
umum tidak sama dengan pelatihan profesi yang memang menyeragamkan
keterampilan khusus.
Satu kurikulum nasional yang tak cuma
berisi pengetahuan-tapi juga menetapkan suatu cara untuk menyampaikannya
kepada seluruh sekolah di Indonesia-tentu aneh. Di samping
keanekaragaman keilmuan seperti diterangkan di atas, keadaan lingkungan
dan masyarakat Indonesia juga sangat beragam.
Sejalan dengan kenyataan ini, idealnya
kurikulum setiap mata pelajaran dirancang dari bawah, yang artinya
perlu berangkat dari keunikan keilmuan. Misalnya, mata pelajaran sejarah
tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran ilmu
pengetahuan alam. Proporsi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap dalam setiap mata pelajaran juga berbeda.
Dengan dasar itu, Kemendikbud
sebaiknya tidak bertindak sebagai penentu kurikulum sekolah, seperti
pesan UU Sisdiknas. Kemendikbud sebaliknya mendorong setiap sekolah,
bahkan setiap pendidik, agar berinovasi mengembangkan kurikulum mata
pelajaran yang menurut nalar mereka paling sesuai. Penghargaan atas
kemandirian ini merupakan pengejawantahan penghargaan bagi
profesionalisme guru.
Kemendikbud cukup menetapkan kerangka
kurikulum serta pengetahuan atau keterampilan paling minimum yang harus
diajarkan sampai akhir jenjang SD, SMP, dan SMA. Ini dapat merujuk pada
standar isi buatan BSNP untuk sementara waktu. Soal kapan harus
mengajarkan materi tertentu, serahkan kepada pendidik.
Kurikulum 2013 sebaiknya dianggap
sebagai sebuah pilihan kurikulum saja. Tak perlu menghabiskan dana,
tenaga, dan waktu lagi untuk membuat penggantinya. Sudah ada beberapa
kurikulum nasional. Dari yang sudah ada saat ini, berikan kebebasan
kepada sekolah dan pendidik untuk memilih kurikulum dan memodifikasinya
agar sesuai dengan keadaan siswa dan sekolah mereka. Perlu pula anjuran
soal keanekaragaman sumber belajar, misalnya dengan anjuran penggunaan
lebih dari satu sumber buku ajar (gratis dan elektronik). Dengan cara
ini, keanekaragaman benar-benar mengejawantah hingga ke inti praktek
pendidikan. Bukankah keanekaragaman itu yang diangankan Presiden Joko
Widodo dalam bidang pendidikan?